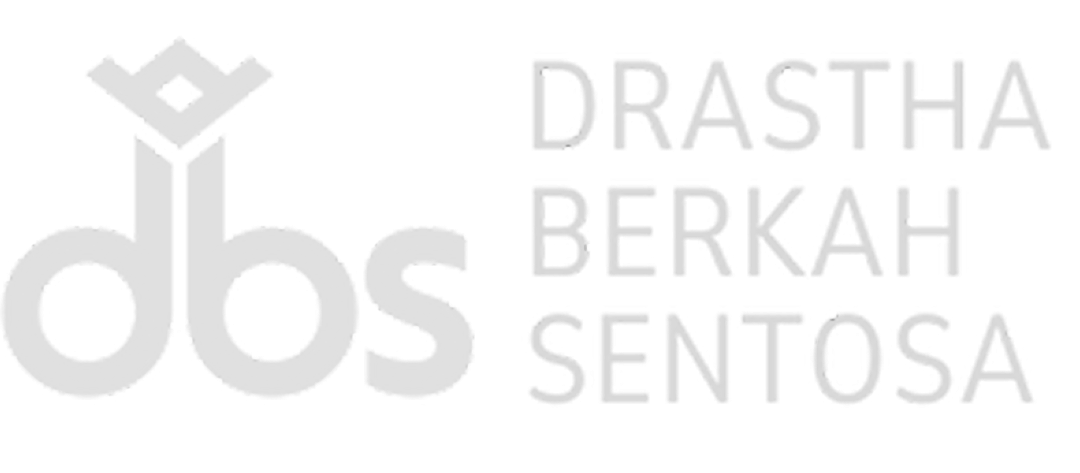Book Appointment Now
Pengguna Media Sosial Dikenakan Pajak?
- On
- InPolitics

Sri mulyani selaku mentri keuangan mengatakan akan memajaki pengguna sosial media
Beberapa tahun terakhir, dunia digital Indonesia menyaksikan ledakan luar biasa dari para content creator yang bermunculan di berbagai platform media sosial. Dari TikTok hingga Instagram, YouTube hingga Facebook, ruang digital telah menjadi arena baru untuk berkarya, berbisnis, dan tentu saja, menghasilkan uang. Namun, di balik layar penuh warna dan kehidupan yang tampak glamor itu, satu hal kini mulai menyelinap masuk: kewajiban membayar pajak.
Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, telah secara resmi menyatakan niatnya untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi digital yang semakin tak terbendung. Bukan sekadar wacana, rencana ini tertuang dalam kebijakan terbaru yang siap diberlakukan mulai tahun 2026, tepatnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh dari media sosial kini secara eksplisit masuk dalam objek pengenaan Pajak Penghasilan.
Kebijakan ini bukan hadir tanpa alasan. Di era ketika satu video viral bisa mengubah nasib seseorang secara finansial, pemerintah melihat peluang besar untuk memperluas basis pajak. Tidak sedikit influencer yang meraup puluhan hingga ratusan juta rupiah dari endorsement, afiliasi, iklan digital, hingga produk yang mereka jual sendiri. Namun ironisnya, tak semua dari mereka tercatat sebagai wajib pajak yang aktif dan patuh. Banyak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum pernah melaporkan penghasilan, bahkan tak tahu bahwa penghasilannya sudah masuk kategori kena pajak.
Untuk menjawab tantangan ini, DJP mulai memanfaatkan teknologi secara lebih agresif. Sistem seperti SONETA (Social Network Analytics) dikembangkan untuk memindai aktivitas para pengguna media sosial secara otomatis. Teknologi ini mampu menghubungkan data digital dengan gaya hidup, popularitas akun, frekuensi promosi berbayar, serta indikasi penghasilan lainnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara profil penghasilan yang seharusnya dilaporkan dengan kenyataan di lapangan, sistem akan memberi sinyal kepada petugas pajak untuk melakukan klarifikasi, pemanggilan, hingga pemeriksaan.
Namun, yang menjadi sorotan dari kebijakan ini bukan hanya teknologinya. Banyak yang bertanya-tanya: apakah semua orang yang bermain media sosial akan dikenai pajak? Jawabannya adalah tidak. Kebijakan ini menyasar para pengguna aktif yang memonetisasi kontennya—mereka yang secara konsisten memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas digital. Seorang pengguna TikTok yang sekadar mengunggah video keluarga tanpa keuntungan komersial tentu tidak akan menjadi objek pajak. Sebaliknya, seorang influencer dengan ribuan pengikut, yang setiap minggu bekerja sama dengan brand, secara otomatis akan dianggap sebagai wajib pajak yang harus patuh pada aturan perpajakan.
Tarif yang dikenakan pun mengikuti sistem pajak penghasilan orang pribadi seperti pada umumnya. Mereka yang memiliki penghasilan bersih tahunan di bawah Rp 60 juta akan dikenai tarif 5 persen. Namun, seiring bertambahnya penghasilan, tarif pajak pun meningkat secara progresif hingga 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar. Dalam beberapa kasus, influencer yang bekerja melalui agensi atau pihak ketiga bisa dikenai PPh Pasal 23, sementara yang menerima penghasilan langsung bisa dikenakan PPh Pasal 21.
Meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan fiskal dan mendorong kepatuhan, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah belum adanya batas penghasilan minimum yang tegas untuk pengenaan pajak digital ini. Banyak kreator mikro yang baru merintis merasa terbebani secara administratif. Mereka harus mengurus NPWP, menghitung pajak, membuat laporan keuangan, dan menghadapi potensi denda, padahal penghasilan mereka belum stabil. Di sinilah kritik mulai bermunculan. Banyak pihak meminta agar pemerintah membuat klasifikasi yang lebih jelas antara kreator besar dan kecil, serta menyediakan insentif atau pelatihan untuk mendukung kepatuhan pajak sejak dini tanpa membebani secara berlebihan.
Aspek lain yang juga mengundang diskusi adalah penggunaan sistem AI dan pemantauan media sosial. Beberapa pihak khawatir bahwa sistem seperti SONETA dapat melanggar privasi atau menyebabkan kesalahan dalam menilai potensi pajak seseorang. Bayangkan jika seseorang yang tampil glamor di media sosial ternyata hanya sekadar menampilkan gaya hidup sewaan demi konten. Apakah sistem bisa membedakan mana yang benar-benar kaya dari yang hanya pura-pura kaya?
Namun demikian, di tengah segala tantangan dan potensi kekurangan, satu hal menjadi jelas: ekonomi digital tidak lagi bisa berjalan tanpa regulasi yang adil. Media sosial telah menjadi bagian dari ekonomi nasional. Dan seperti sektor ekonomi lainnya, ia pun harus ikut berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan pajak yang dikelola secara transparan, edukasi yang memadai, dan sistem yang adil, para pelaku ekonomi digital seharusnya bisa melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
Seiring waktu berjalan menuju 2026, bola kini ada di tangan pemerintah dan masyarakat digital. Sosialisasi harus dilakukan secara masif. Komunitas kreator perlu dilibatkan dalam dialog. Mekanisme pemantauan harus transparan dan adil. Hanya dengan pendekatan menyeluruh seperti itu, kebijakan pajak media sosial bisa berjalan dengan baik—bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi sebagai cermin kesadaran fiskal bangsa yang tumbuh bersama teknologi.
Newsletter Updates
Enter your email address below and subscribe to our newsletter